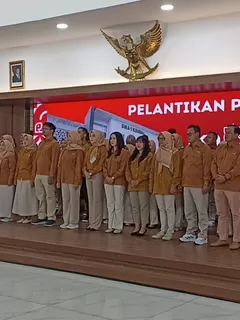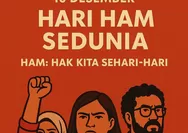Dilansir dari Kompas.com, Bank Dunia (World Bank) bersedia menggulirkan US$30 miliar atau Rp 441 miliar (kurs Rp 14.700) sebagai respon dalam upaya mengatasi krisis ketahanan pangan global. Dana tersebut disediakan untuk pembiayaan sektor pangan, pertanian, nutrisi, perlindungan sosial, air, dan irigasi selama 15 bulan ke depan.
Dana penyaluran ini mencakup biaya peningkatan produksi pangan dan pupuk, perbaikan sistem pangan, fasilitasi peningkatan perdagangan, serta sebagai dana sokongan bagi keluarga dan produsen rentan.
Presiden Grup Bank Dunia David Malpas baru-baru ini mengatakan tanggapannya terhadap kenaikan harga pangan yang luar biasa itu. Dilansir dari BBC, Jumat 21 April 2022. Bank Dunia memperkirakan harga pangan dapat meroket tajam hingga 37%. Naiknya harga
pangan sangat berdampak pada masyarakat ekonomi rendah dan terentan. Ini, tentu saja dapat mendorong ratusan juta orang ke dalam kemiskinan dan kekurangan gizi jika krisis terus berlanjut. Malpas mengatakan negara-negara di seluruh dunia perlu meningkatkan produksi pangan di masa depan sebagai respon terhadap krisis pangan akibat terjadinya invasi Rusia ke Ukraina sejak akhir Februari.
Oleh karena itu, adanya pembiayaan yang diberikan oleh Bank Dunia dapat membantu. Negara-negara harus berupaya bersama dalam melakukan peningkatan pasokan energi dan pupuk, membantu petani meningkatkan tanam dan hasil panen, serta menghapus kebijakan yang menghambat ekspor dan impor.
Melihat besarnya upaya dunia dalam mengatasi krisis ketahanan pangan, bukankah ini bisa menjadi motivasi bagi Indonesia untuk membangkitkan kembali kejayaan swasembada pangannya? Kita semua tahu bahwa Indonesia terkenal dengan julukannya sebagai negara agraris, bahkan ada ungkapan “Gemah ripah loh jinawi”. Gemah ripah loh jinawi adalah ungkapan yang menggambarkan betapa berlimpahnya kekayaan alam Indonesia.
Baca Juga: Banjir Rob di Semarang Hari Ini Disebut Terbesar Sejak 2002
Dan kita juga sering mendengar bahwa alam Indonesia memanglah berlimpah, hingga muncul juga ungkapan dalam sebuah lagu, “Tanah kita tanah surga, batu, dan tongkat jadi tanaman”.
Ditambah lagi, Indonesia pernah berada pada era kebanggaan dimana Indonesia berhasil dengan swasembada berasnya. Era tersebut terjadi pada masa kepepimpinan Presiden Soeharto, yang pada tahun 1984 Indonesia berhasil memproduksi 25,8 juta ton beras. Padahal, pada tahun 1969, Indonesia hanya mampu memproduksi 12,2 juta ton beras, sehingga memaksa
Indonesia untuk mengimpor setidaknya 2 juta ton beras setiap tahun.
Sejak berlalunya swasembada beras pada tahun 1984, Indonesia sebenarnya telah menjadi pengimpor neto beras, dengan permintaan impor hampir 4 persen selama 15 tahun terakhir. Selama 15 tahun terakhir, Indonesia mengalami sejumlah krisis pangan dan masuk
dalam daftar 10 pengimpor terbesar bahan pangan strategis seperti beras, kedelai, tepung, dan gula, yang semuanya kini mengalami kenaikan harga pada pasar global. Pertanyaannya saat ini, mampukah Indonesia membalikkan keadaan dan menjadi salah satu pemenang dari krisis ketahanan pangan global dengan memanfaatkan sektor pertanian dan peluang kenaikan harga komoditas pada pasar global?
Logikanya, kenaikan harga pasar global dan kenaikan harga domestik akan memotivasi petani untuk meningkatkan produksinya. Namun, hal itu tidak akan terjadi begitu saja. Penurunan produksi beras dan produk pangan lainnya selama ini terhambat disebabkan petani kehilangan semangat bercocok tanam, yang dalam banyak kasus yang menjadi pemicunya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri.
Dengan kata lain, jika ingin menjaga kebertahanan swasembada pangan, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi produksi pangan.
Demi menciptakan swasembada pangan, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan produktivitas (baik lahan maupun tenaga kerja), meningkatkan teknologi pertanian, menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, dan obat-obatan), perbaikan infrastruktur dan kelembagaan pertanian, membenahi rantai pasokan pemasaran dan distribusi, serta revitalisasi kegiatan penelitian dan aturan perdangan. Dalam hal beras, melihat pengalaman swasembada tahun 1984 menunjukkan bahwa swasembada pangan melalui swasembada beras tidaklah mustahil untuk dicapai kembali jika mau berusaha.
Dari aspek sumberdaya lahan, menurut data Kementerian Pertanian, masih ada peluang besar untuk pembukaan lahan pertanian, termasuk pemanfaatan lahan terlantar yang ada. Dari luas 190 juta hektar daratan di Indonesia, sekitar 101 juta hektar dapat dikembangkan untuk pertanian tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan. Dari luas kawasan itu, hanya sekitar 64/69,15 juta yang digunakan sebagai lahan pertanian. Dari jumlah itu pun, hanya terdiri 7,7 juta hektar lahan sawah, 10,6 juta hektar lahan tadah hujan, 19,6 juta hektar perkebunan rakyat dan swasta, 9,4 juta hektar lahan kayu-kayuan, dan 12,4 juta hektar berupa semak belukar atau hanya berupa hamparan alang-alang.
Permasalahannya, tidaklah mudah mengubah lahan terlantar yang tercecer di berbagai provinsi menjadi lahan pertanian. Dimulai dari masalah status tanah yang kurang jelas, hingga persoalan biaya yang dikeluarkan yang tidak sebanding secara ekonomis.
Padahal dalam kenyataannya, ketika keadaan sebagian besar lahan pertanian mengalami penurunan kesuburan, ekstenfikasi menjadi cara tepat untuk meningkatkan produksi. Stagnasi teknologi pertanian tidak secara signifikan meningkatkan produktivitas yang
dicapai dalam satu dekade terakhir. Minimnya teknologi pascapanen juga mengakibatkan upaya pengurangan angka kehilangan panen sebesar 20 persen menjadi tidak terlaksana di lapangan.
Belum lagi faktor lain, seperti konversi lahan pertanian yang mencapai 120.000 hektar per tahun. Padahal sebagian dari lahan yang dikonversi ini merupakan lahan irigasi yang subur dan sangat produktif. Namun, persetujuan terus terjadi untuk pengalihan peruntukan,
terutama untuk infrastruktur, permukiman, industri, dan pertambangan.
Dari sisi petani sendiri, insentif harga dan kelembagaan pertanian yang ada membuat petani tidak memungkinkan untuk menjalankan usaha tani yang menguntungkan. Secara nasional, nilai tukar petani (HTP) memang terus meningkat. Namun jika dicermati lebih jauh, peningkatan tersebut sebagian besar terjadi di luar Jawa, dan kenaikan harga akibat lonjakan harga komoditas dunia kebanyakan keuntungannya hanya dapat dirasakan oleh pengusaha perkebunan besar yang menikmati keuntungan cukup besar.
Baca Juga: Besek Bekas Jadi Action Figure, Karya Pemuda Batang Ini Laku hingga Singapura
Beberapa kritik terhadap kebijakan beras atau kebijakan ketahanan pangan (dalam banyak kasus hanya melanjutkan kebijakan era Soeharto) adalah bahwa kebijakan tersebut lebih banyak biasnya terhadap kepentingan konsumen, bukan pada kepentingan petani. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi mengingat sebagian besar petani kita adalah net comsumer dimana mereka lebih banyak mengkonsumsi daripada memproduksi. Mayoritas petani Indonesia atau sekitar 75 persen adalah buruh tani atau hanya petani kecil yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar.
Ke depan, kebijakan terkait pertanian dan ketahanan pangan harus memposisikan petani sebagai sentral. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan reformasi pertanian dengan meningkatkan akses petani terhadap lahan dan air, yang hal tersebut sejak awal dicanangkannya tidak terlaksana dengan baik. Kebijakan beras atau ketahanan pangan pemerintah yang selama ini ditempuh seringkali hanya dibuat pada tingkat nasional, padahal permasalahannya sendiri terdapat pada tingkat lokal atau rumah tangga (daya beli).
Selain itu, permasalahan lainnya adalah kebijakan yang diambil cenderung hanya bersifat reaktif dari segi waktu, lambat, dan ad hoc. Fenomena banyaknya pengusaha besar yang terjun ke bidang pertanian, termasuk pertanian pangan, menunjukkan bahwa sektor pertanian termasuk pertanian pangan, justru sangat berpotensi untuk dikembangkan.
Bahkan, bukan tidak mungkin jika krisis pangan global
serta kenaikan harga pangan dan kodomitas di pasar global saat ini dapat dijadikan momentum kebangkitan sektor pertanian Indonesia. Hal ini penting mengingat peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian. Terlebih lagi, 44 persen penduduk kita bergantung secara langsung dan tidak langsung pada sektor ini untuk kehidupan mereka.